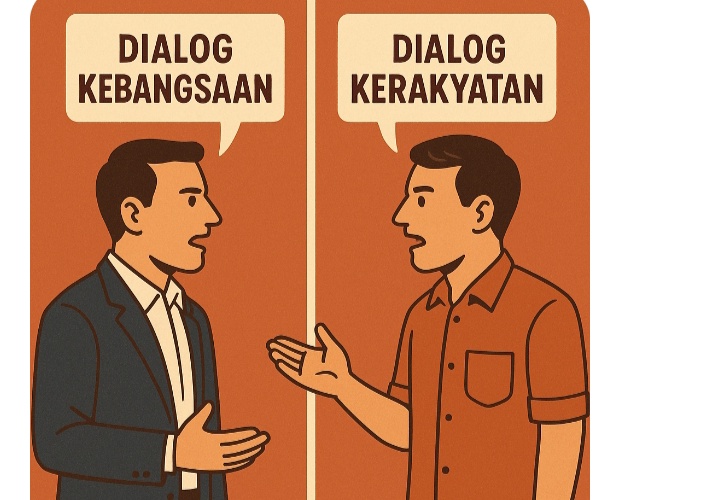Oleh: Maghfur Ghazali
DI TENGAH arus deras perubahan sosial, polarisasi politik, dan tekanan ekonomi yang terus menghimpit rakyat kecil, ajakan untuk memperkuat dialog kebangsaan kembali digaungkan oleh banyak pihak. Dalam berbagai forum resmi, pernyataan seragam terus diulang: “Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.” Sebuah seruan yang tampaknya baik, namun sayangnya kerap terasa hampa karena terlalu jauh dari realitas yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Di saat sebagian elite sibuk membicarakan makna persatuan dari balik panggung megah, rakyat di bawah justru bertanya-tanya: “Apakah suara kami masih didengar?” Di sinilah muncul urgensi sebuah pendekatan lain: dialog kerakyatan, sebuah dialog yang lebih membumi, lebih jujur, dan lebih mendengarkan daripada menggurui.
Dialog kebangsaan, seperti yang selama ini kita kenal, sering kali beroperasi dalam ruang formal dan dikendalikan oleh narasi elite. Tema-tema besar seperti nasionalisme, toleransi, dan pluralisme diangkat tinggi-tinggi, namun sayangnya jarang dikaitkan langsung dengan kebutuhan mendesak masyarakat: harga bahan pokok yang melambung, pendidikan yang tak merata, ketimpangan sosial, dan pengangguran.
Kita seolah lupa bahwa cinta tanah air tidak tumbuh dari doktrin, tapi dari rasa aman dan sejahtera sebagai warga negara. Seperti kata Paulo Freire, seorang pemikir pendidikan dari Brasil dalam Education for Critical Consciousness: Warga negara tidak bisa belajar mencintai bangsanya jika ia terus dipinggirkan dari percakapan tentang masa depan bangsa itu.
Dialog kebangsaan memang penting, tetapi ketika ia menjadi terlalu simbolik dan hanya menjadi ajang afirmasi sepihak tanpa refleksi kritis dan keterlibatan rakyat secara utuh, maka ia kehilangan maknanya.
Sebaliknya, dialog kerakyatan menempatkan rakyat sebagai subjek utama. Ia tidak berlangsung di hotel berbintang, melainkan di balai desa, di warung kopi, di kelompok tani, bahkan di kolong jembatan tempat kaum marjinal menggantungkan hidupnya.
Dialog kerakyatan membuka ruang untuk mendengarkan cerita-cerita dari bawah—tentang sawah yang gagal panen, tentang anak putus sekolah, tentang internet yang tak memiliki koneksi data, tentang penambahan ruang kuliah yang tak kunjung selesai, tentang buruh yang dirumahkan dan banyak lag, juga tentang harga-harga yang terus naik dls.
Mendengar rakyat bicara tentang hidup mereka sendiri bukan hanya tindakan empati, tetapi juga fondasi demokrasi yang sejati. Rakyat tidak hanya ingin didengar saat pemilu mendekat, mereka ingin didengar setiap hari. Inilah mengapa dialog kerakyatan menjadi semakin relevan.
Bung Hatta, salah satu proklamator bangsa kita pernah berkata; Indonesia merdeka bukan tujuan akhir, melainkan jembatan untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dialog kerakyatan adalah proses menyeberangi jembatan itu bersama rakyat, bukan meninggalkan mereka di belakang.
Realitas hari ini menunjukkan ketimpangan makin menganga. Data kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Akses layanan publik masih belum merata. Banyak warga merasa terpinggirkan dari proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Dalam kondisi ini, memperbanyak dialog kerakyatan justru menjadi strategi paling mendasar untuk membangun kepercayaan publik terhadap negara dan pemimpinnya.
Rakyat tidak membutuhkan orasi tentang toleransi jika harga beras terus naik. Mereka tidak butuh pidato panjang soal cinta NKRI jika suara dan aspirasinya terus diabaikan. Mereka butuh ruang berbicara. Butuh pemimpin yang mau mendengar, bukan sekadar berbicara.
Tentu, dialog kebangsaan tidak harus ditinggalkan. Namun ia perlu ditopang oleh kekuatan dialog kerakyatan. Justru dalam situasi negara yang terpecah secara sosial dan politik seperti sekarang, dialog kebangsaan akan lebih kuat jika ia tumbuh dari akar rumput—bukan hanya dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas.
Yang kita perlukan saat ini adalah keberanian para pemimpin untuk turun mendengar, bukan hanya tampil di podium. Seperti ungkapan klasik: “Kalau ingin membangun menara yang kokoh, kuatkan dulu pondasinya.” Rakyat adalah pondasi bangsa ini. Dan mereka sudah lama ingin didengar.
Bangsa ini tidak kekurangan pidato persatuan. Yang kurang adalah keadilan. Yang langka adalah keberanian untuk mendengarkan jeritan dari lapisan paling bawah. Maka dalam situasi seperti sekarang, dialog kerakyatan bukan hanya pelengkap, tapi kebutuhan mendesak. Kita bisa bicara tentang Pancasila sepanjang hari, tapi jika rakyat tidak merasakan kehadiran negara dalam hidupnya, mereka akan merasa menjadi warga kelas dua di negeri sendiri.
Dialog kerakyatan adalah jalan sunyi yang mungkin tidak sepopuler seminar kebangsaan. Tapi justru dari jalan sunyi itulah, bangsa ini bisa menemukan kembali ruhnya. []
[Penulis adalah Dosen Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Institut K.H. Noer Alie (IAN) Bekasi]