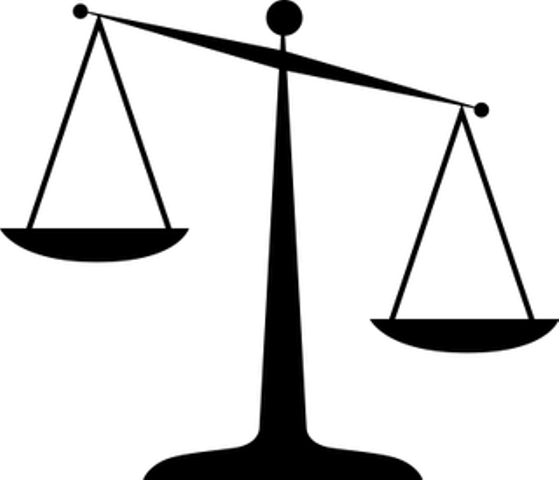NETRALITAS nampaknya menjadi sebuah kata penuh makna yang lebih mudah mengucapkan dari pada mempraktikkannya. Apalagi dalam suasana menjelang kampanye pemilihan presiden saat ini.
Netralitas itulah yang diingatkan Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono di depan sejumlah perwira TNI dan Polri awal pekan ini. Penyampaiannya cukup keras, karena dilatari adanya informasi atau laporan bahwa ada pihak-pihak yang mencoba mengajak anggota TNI dan Polri mendukung salah satu pasangan calon presiden – calon wakil presiden.
Netralitas, sebagai sikap yang tak berpihak — yang bila diterjemahkan langsung terkait Pilpres adalah tak berpihak ke pasangan Jokowi dan JK maupun ke Prabowo dan HR — seharusnyalah diusung dan dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga negara. Tak saja TNI dan Polri, tapi juga lembaga lain seperti DPR/MPR dan DPD, termasuk perguruan tinggi. Bahkan lembaga-lembaga lain yang selama ini eksis di tengah masyarakat dengan menyebut diri sebagai lembaga publik atau sering mengatasnamakan tindakannya demi kepentingan publik.
Dalam konteks inilah kita menelaah munculnya desakan dari kelompok masyarakat kepada DPR RI agar segera memanggil Panglima TNI, untuk membuka dokumen Dewan Kehormatan Perwira yang berisi dasar dan pertimbangan pemecatan Letjen Prabowo Subianto sebagai anggota TNI.
Prabowo Subianto adalah calon presiden pada Pilpres yang segera digelar Juli bulan depan. Prabowo dan pasangannya adalah calon presiden yang kini sedang berjuang, atau dalam bahasa lain ‘’bertarung’’ memperebutkan hati rakyat pemilih, rakyat Indonesia, untuk dipercaya memegang tampuk pimpinan negeri ini selama lima tahun ke depan.
Karenanya, sulit untuk menghindarkan kita dari pertanyaan, bukankah desakan agar DPR memanggil Panglima TNI terkait dasar dan pertimbangan pemecatan Prabowo dari TNI adalah sikap yang jauh dari netralitas?
Kita memang dapat memahami tujuan desakan tersebut, yaitu untuk menguak kebenaran dari kasus penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis pada 1997 – 1998.
Perlu digarisbawahi, tuntutan untuk menguak kebenaran, tentu tak kenal henti, sampai kapan pun. Karena, pengungkapan kebenaran yang tertunda-tunda terus, di satu sisi hanya akan menjadi beban dan utang sejarah bagi siapa pun kelak yang akan memimpin negeri ini. Sementara di sisi lain, tertundanya pengungkapan kebenaran itu sendiri tak akan pernah memberi kepastian kepada orang yang disangkakan.
Tapi, haruskah upaya pengungkapan kebenaran itu didesakkan saat ini juga, saat kampanye Pilpres baru saja akan dimulai? Kenapa tak sabar menunggu Pilpres selesai yang nota bene kurang lebih satu bulan lagi ? Kenapa sebelum-sebelum ini, bahkan ketika Pilpres lima tahun lalu hal ini didiamkan? Atau memang, desakan ini adalah sebuah keberpihakan yang jelas kepada salah satu capres?
Banyak pertanyaan, dan banyak argumen sebagai jawaban yang mungkin muncul terkait desakan pengungkapan kebenaran kasus penculikan dan penghilangan paksa ini. Namun satu hal yang tak boleh dilupakan adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Masyarakat tentu dapat menilai, dan masyarakat menuntut itu, terutama dari mereka yang oleh masyarakat diberi predikat intelektual.
Dalam pertarungan Pilpres sekarang ini, bukan tak mungkin terpaan betubi-tubi yang dialamatkan kepada seorang calon — seperti soal pelanggaran HAM, soal penculikan dan penghilangan paksa, soal penolakan Amerika Serikat – sebagai kampanye negatif yang justru berbuah manis kepada calon tersebut. Bukankah sejak sepuluh tahun belakangan ini di tengah masyarakat kita muncul fenomena, orang akan berpihak kepada yang dianggap terzalimi? Mari merenungkannya. (***)